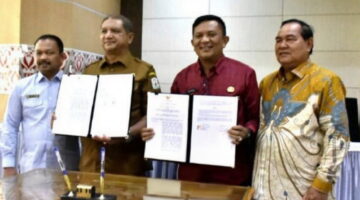MEULABOH — Di tengah riuh baliho dan seremoni seremonial yang mengklaim keberhasilan program tanggung jawab sosial perusahaan, suara nyaring dari kalangan mahasiswa justru mengusik klaim itu. Putra Rahmat, Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU), tak ragu menyebut Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan PT Mifa Bersaudara sebagai praktik yang lebih menonjolkan pencitraan ketimbang komitmen sosial.
“PT Mifa menolak diaudit. Itu saja sudah cukup menjadi ukuran bahwa mereka tidak transparan,” ujar Putra, Selasa, 9 Juli 2025.
Kalimat itu bukan sekadar ekspresi kekecewaan. Di baliknya tersimpan kemuakan terhadap praktik tambang yang dianggap telah lama menafikan hak publik untuk tahu: ke mana dana CSR digelontorkan, bagaimana distribusinya, dan apa dampaknya bagi warga sekitar wilayah tambang.
Putra menuding PT Mifa, perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Aceh Barat, bersikap tertutup dan enggan membuka laporan CSR mereka ke publik. Penolakan terhadap audit eksternal terhadap dana CSR, yang sempat memicu perdebatan beberapa waktu lalu, menurutnya merupakan refleksi dari logika perusahaan yang rapuh dan defisit kepercayaan diri.
“Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa takut diaudit?” ucapnya. “Alih-alih menjawab dengan data dan keterbukaan, mereka malah sibuk membantah tudingan tanpa memberi bukti yang bisa diuji.”
Kritik ini dilontarkan menyusul minimnya kontribusi CSR PT Mifa dalam ajang Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) se-Aceh yang digelar di Meulaboh — tepat di jantung wilayah operasi mereka. Menurut data yang diterima mahasiswa, kontribusi perusahaan hanya berkisar Rp70 juta. Jumlah yang disebut Putra sebagai ironi: kecil, jika dibandingkan skala acara dan lokasi pelaksanaannya yang berada persis di daerah tambang.
“Saya justru menduga ada kampus di luar Aceh Barat yang menerima CSR lebih besar untuk acara yang skalanya tak sebesar ini,” katanya. “Ini menunjukkan ketimpangan yang parah, dan perusahaan tampak tidak peka terhadap lingkungan sosial terdekat mereka.”
Bagi Putra, pendekatan CSR PT Mifa terlalu elitis. Mereka dinilai lebih mengedepankan penerimaan dari kelompok penerima langsung ketimbang membuka ruang evaluasi dari publik luas. “Kalau yang ditanya hanya penerima manfaat, tentu semua akan bilang ‘bermanfaat’. Tapi siapa yang mengukur dampak negatif dari aktivitas tambang?” ujarnya.
Putra menyebut ketimpangan ini bukan hanya soal angka bantuan atau lokasi pemberian dana. Lebih jauh, ia menyoal ketidakseimbangan antara dampak buruk yang ditimbulkan aktivitas tambang dan manfaat yang diklaim melalui program CSR. Menurutnya, beasiswa dan bantuan sosial tidak bisa menambal kerusakan ekologis, ketimpangan sosial, dan ancaman kesehatan yang dihadapi masyarakat.
“Kalau mau jujur dihitung, saya yakin dampak negatif jauh lebih besar daripada manfaat yang mereka kampanyekan,” katanya.
Ia menyebut baliho-baliho besar dan iklan-iklan media tentang kontribusi CSR sebagai semata-mata alat legitimasi. Seremoni dan simbolisasi dipoles sedemikian rupa agar publik lupa pada inti persoalan: kerusakan yang ditinggalkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab.
“Ini bukan soal berapa banyak beasiswa yang diberikan atau acara apa yang mereka danai. Ini soal model relasi ekonomi-politik yang eksploitatif. CSR tidak boleh jadi kedok untuk menutupi luka sosial dan ekologis yang ditinggalkan industri tambang,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Putra juga menyerukan agar Pemerintah Aceh mengevaluasi ulang, bahkan mencabut izin operasi PT Mifa Bersaudara. Ia menyebut sudah saatnya rakyat Aceh mengelola sumber daya alamnya sendiri dengan cara yang adil dan berkelanjutan.
“Kita punya kekhususan. Tapi kekhususan itu tak ada artinya kalau perusahaan tambang masih memperlakukan Aceh sebagai wilayah taklukan,” ujarnya. “Apa gunanya otonomi jika yang kita panen cuma kerusakan dan sisa hasil produksi?”
Seruan Putra menambah deretan panjang kritik terhadap aktivitas pertambangan di Aceh yang belakangan semakin mendapat sorotan. Di banyak tempat, narasi “pembangunan lewat pertambangan” mulai kehilangan daya. Yang tersisa hanyalah debu, lubang tambang, dan keresahan panjang tentang masa depan ruang hidup. (*)