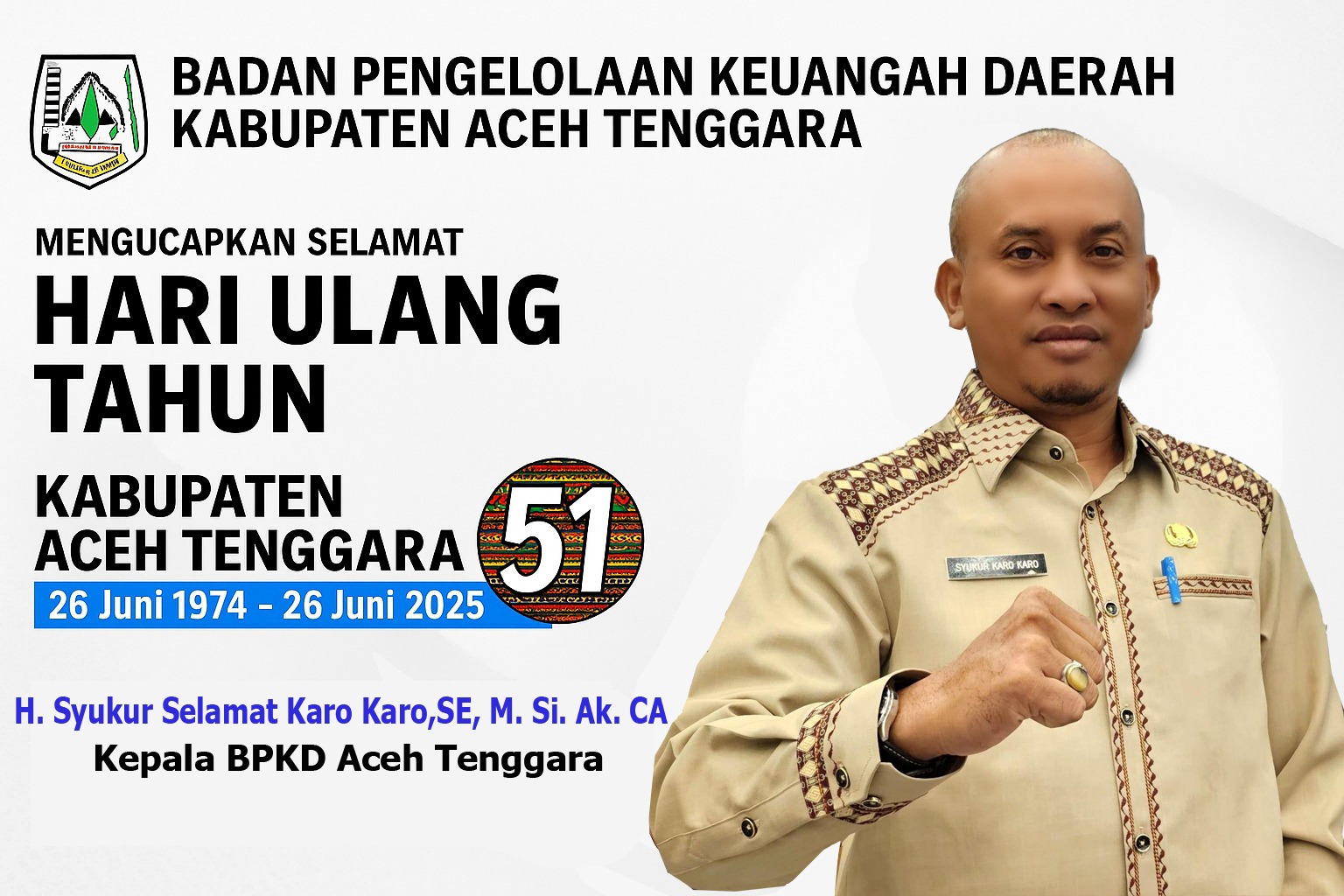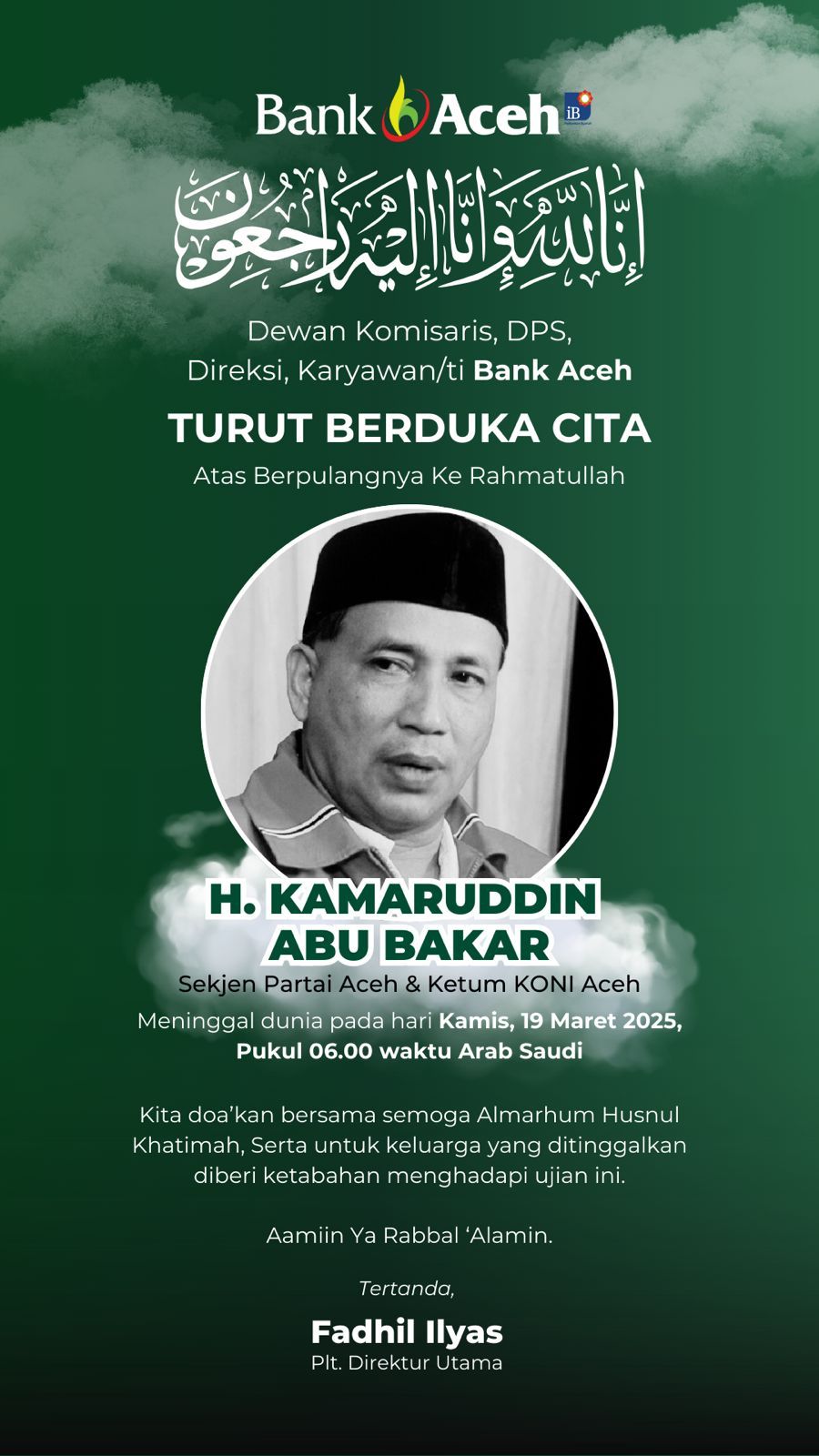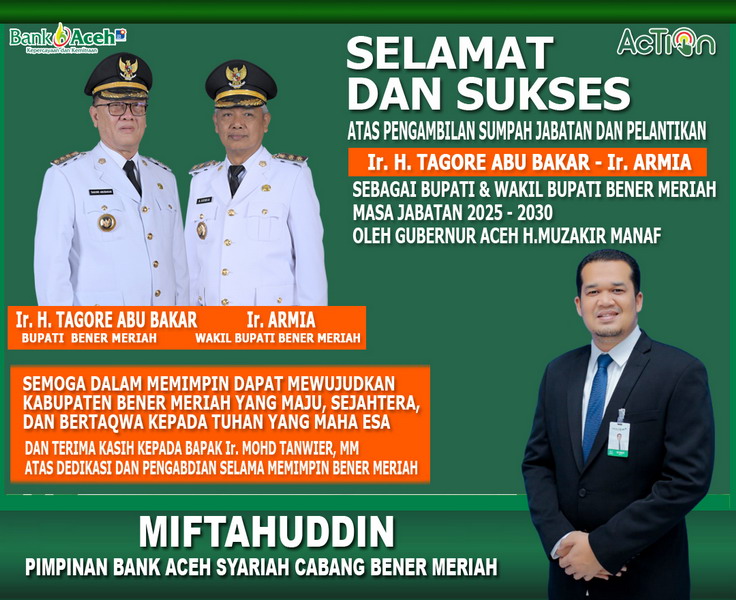Oleh: Asma Sulistiawati (Pegiat Literasi)
Bayangkan sebuah tempat di mana langit biru membentang tanpa kabut asap, laut sebening kristal membelai pasir putih, dan hutan tropis masih bergema dengan nyanyian alam yang tak terjamah. Sebuah surga yang belum tersentuh kerusakan besar akibat eksploitasi manusia, sebuah titik penting bagi keanekaragaman hayati dunia, dan warisan hidup bagi masyarakat adat yang sudah berabad-abad menjaga keseimbangan alamnya. Tempat itu benar-benar ada — namanya Raja Ampat.
Terletak di ujung timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua Barat, Raja Ampat sering disebut oleh para ilmuwan sebagai “The Last Paradise on Earth”. Pulau-pulau kecil dengan lanskap karst yang menakjubkan dan perairan yang menjadi rumah bagi lebih dari 1.800 spesies ikan dan 600 jenis karang yang berbeda, menjadikan kawasan ini salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Keunikan ekosistemnya telah menarik perhatian dunia internasional, dari peneliti biologi laut hingga aktivis lingkungan.
Namun, surga yang selama ini menjadi simbol keindahan alam dan kekayaan hayati Indonesia ini kini menghadapi ancaman besar yang datang bukan dari kekuatan alam, melainkan dari tangan manusia sendiri. Ancaman ini datang dibalut klaim pembangunan dan kemajuan, yang menjadikan ekosistem Raja Ampat sebagai target eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan ekonomi. Di balik kata “pembangunan” dan “investasi”, terselip risiko kerusakan permanen yang dapat menghilangkan keajaiban alam ini selamanya.
Isu Tambang Nikel: Ketika Surga Terancam oleh Kepentingan Ekonomi
Pada Juni 2025, perhatian nasional dan internasional tertuju pada Raja Ampat ketika isu tambang nikel di kawasan tersebut kembali mencuat. Perusahaan tambang PT Anugerah Tambang Smelter (ATS), yang sejak Mei 2024 telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) seluas 13.000 hektar di Pulau Kawe, mulai melakukan aktivitas eksplorasi yang mengancam kelestarian pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Kawe, Gag, Batang Pele, Manuran, dan Manyaifun.
Sementara pemerintah pusat mendorong hilirisasi mineral demi mendukung transisi energi nasional dan industri kendaraan listrik berbasis baterai, konsekuensi sosial dan ekologis dari eksploitasi tambang ini mulai terlihat jelas. Aktivitas tambang membawa dampak serius terhadap ekosistem laut dan hutan yang selama ini terjaga, sekaligus mengganggu kehidupan masyarakat adat yang telah lama hidup selaras dengan alam.
Di tengah event Indonesia Critical Minerals Conference yang berlangsung di Jakarta pada 3 Juni 2025, sekelompok aktivis Greenpeace bersama empat pemuda Papua dari Raja Ampat melakukan aksi damai sebagai bentuk protes simbolik. Mereka membentangkan spanduk dengan pesan “What’s the True Cost of Your Nickel?” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”. Aksi ini menarik perhatian media dan publik karena berhadapan langsung dengan narasi besar pemerintah tentang pentingnya energi hijau dan kemandirian industri mineral.
Dampak Sosial dan Lingkungan yang Nyata
Tidak hanya aktivis lingkungan yang bersuara, masyarakat adat Raja Ampat pun mulai terdorong untuk melawan. Ronisel Mambrasar, juru bicara Aliansi Jaga Alam Raja Ampat, mengungkapkan keresahannya: “Kami hidup damai, tenang, dan sejahtera. Namun sejak tambang masuk, mulai muncul konflik antarwarga. Ini bukan hanya soal alam yang rusak, tapi juga soal peradaban kami yang terancam punah.”
Kehadiran perusahaan tambang telah merusak harmoni sosial yang selama ini dijaga masyarakat adat. Ketidakseimbangan ekonomi, tekanan lingkungan, dan perubahan pola hidup menyebabkan ketegangan dan perpecahan yang tidak mudah diperbaiki. Kondisi ini berpotensi memicu krisis sosial yang berkepanjangan, di mana masyarakat yang dulu menjadi penjaga utama alam berubah menjadi korban dari sistem yang mengabaikan hak dan kearifan lokal.
Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, turut menyampaikan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa 97% wilayah Raja Ampat adalah kawasan konservasi, yang seharusnya dilindungi dari aktivitas pertambangan. Namun, izin usaha pertambangan dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat tanpa koordinasi memadai dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. “Kami meminta agar IUP yang berada di wilayah konservasi tersebut dikaji ulang demi menjaga kelestarian dan keberlanjutan wilayah ini,” ujarnya. (Bisnis.com Hijau, 3 Juni 2025)
Konflik Hukum dan Etika Lingkungan
Kawasan Pulau Kawe dan Gag sendiri telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Papua Barat No. 10 Tahun 2019 dan termasuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang secara tegas tidak mengizinkan aktivitas pertambangan. Dengan demikian, eksploitasi tambang nikel di kawasan ini sangat problematis dari segi hukum dan etika lingkungan.
Namun, sistem kapitalisme neoliberal yang menempatkan alam sebagai komoditas membuat aturan dan regulasi menjadi rentan dilanggar. Siapa yang memiliki modal dan koneksi politik bisa memperoleh izin dan mengelola sumber daya alam demi keuntungan bisnis semata, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat lokal.
Nikel, yang dipandang sebagai bahan baku utama untuk industri baterai kendaraan listrik dan energi hijau, sering dianggap sebagai “harapan masa depan”. Namun ironisnya, mayoritas smelter nikel di Indonesia, sekitar 80%, dikuasai oleh perusahaan asing, terutama dari Tiongkok. Ini berarti nilai tambah ekonomi yang seharusnya dapat memberdayakan masyarakat dan negara, justru mengalir keluar negeri. Sementara masyarakat lokal hanya menerima dampak negatif seperti pencemaran, konflik sosial, dan kerusakan ekosistem yang sulit diperbaiki.
Dilema Transisi Energi dan Ekologi
Narasi “transisi energi” dan “green economy” memang penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi krisis iklim global. Namun, cara kita menjalankan transisi ini harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak menciptakan kerusakan baru yang justru merusak keseimbangan alam.
Bagaimana mungkin menyelamatkan dunia dari pemanasan global, jika kita mematikan paru-paru dunia lain? Hutan, laut, dan ekosistem laut Raja Ampat yang selama ini menjadi penyerap karbon alami dan pelindung keanekaragaman hayati, kini justru dalam ancaman rusak akibat aktivitas tambang yang menghancurkan habitat dan merusak ekosistem.
Saksi nyata kerusakan akibat tambang bisa dilihat dari daerah-daerah lain seperti Obi, Weda, atau Morowali. Di sana, masyarakat menghadapi polusi air dan udara, banjir akibat penggundulan hutan, gagal panen, dan kenaikan harga tanah yang tidak terkendali. Ruang hidup dan budaya masyarakat juga tergerus, bahkan generasi muda kehilangan harapan karena lingkungan dan ekonomi yang memburuk. Pola ini hendak diulang di Raja Ampat, yang mestinya menjadi contoh keberlanjutan.
Masyarakat Adat: Penjaga dan Korban
Yang lebih tragis, masyarakat adat yang selama ratusan tahun menjaga hutan dan laut Raja Ampat mulai kehilangan tanah dan identitasnya. Mereka adalah mitra alam yang memahami cara memelihara keseimbangan ekologi, tetapi kini suaranya hampir terabaikan. Tanah adat mereka tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber pangan, tapi juga pusat budaya dan spiritual yang menjadi jiwa komunitas.
Pengabaian hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah pengkhianatan terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia. Negara dan perusahaan tidak boleh mengesampingkan keberadaan dan hak masyarakat adat demi keuntungan ekonomi.
Perlu Paradigma Baru: Islam dan Konsep Kepemilikan Umum
Solusi dari krisis ini tidak cukup hanya dengan perbaikan regulasi parsial atau kampanye lingkungan. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma yang mendasar terhadap cara kita memandang alam dan pembangunan.
Dalam perspektif Islam, alam adalah titipan Allah (amanah) yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Sumber daya alam strategis seperti tambang, hutan, dan air adalah milik umum (milkiyyah ‘ammah), yang tidak boleh dimiliki atau dikomersialisasi secara eksklusif oleh individu atau korporasi.
Negara berperan sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mendistribusikan hasil pengelolaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Perusakan lingkungan dilarang keras dan dianggap dosa besar dalam syariat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya” (QS. Al-A’raf: 56).
Sejarah Khilafah Islam mengenal konsep “hima”, yaitu wilayah khusus yang dilarang untuk dimanfaatkan secara berlebihan demi menjaga kelestarian ekosistem. Konsep ini dapat dijadikan inspirasi untuk menjaga kawasan konservasi seperti Raja Ampat.
Bayangkan jika prinsip-prinsip ini diterapkan: tidak ada tambang yang merusak hutan dan laut Raja Ampat, masyarakat adat menjadi mitra utama dalam menjaga bumi, dan pembangunan dijalankan dengan prinsip merawat dan menumbuhkan, bukan menghancurkan demi keuntungan sesaat.
Penutup: Saatnya Berdiri Membela Raja Ampat
Raja Ampat masih bisa diselamatkan, tetapi waktu tidak banyak. Ketika izin tambang sudah keluar dan alat berat mulai masuk, kerusakan yang terjadi akan sangat sulit, bahkan nyaris mustahil, untuk dipulihkan.
Maka sekarang, bukan besok, kita harus bersuara. Tidak hanya lewat kampanye atau demonstrasi, tetapi juga dengan membangun kesadaran kritis terhadap sistem yang selama ini mengizinkan kerusakan ini berlangsung. Keberanian menuntut perubahan paradigma yang adil dan berkelanjutan harus menjadi komitmen kita bersama.
Raja Ampat tidak membutuhkan belas kasihan. Ia membutuhkan pembela yang teguh dan cerdas, yang berani melawan sistem yang merusak dan memilih jalan yang sesuai dengan nilai keadilan dan amanah syariat. Siapakah yang akan berdiri membelanya?
Wallahu’alam.