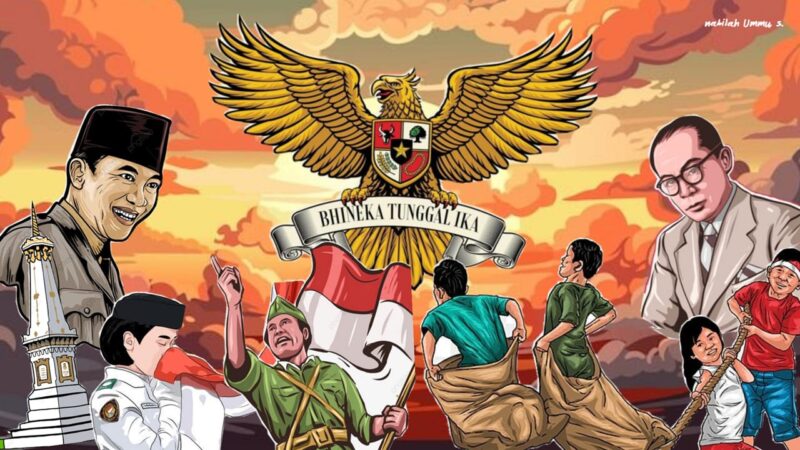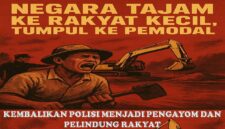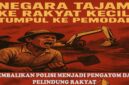Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Perdebatan mengenai arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru ketika sejumlah lembaga kajian, termasuk CSIS, menyoroti kecenderungan resentralisasi kewenangan. Kritik tersebut berangkat dari pandangan bahwa beberapa langkah politik dan kebijakan di awal pemerintahan mengindikasikan menguatnya kontrol pemerintah pusat atas daerah. Kekhawatiran ini bukan lahir dari ruang kosong, sejarah politik Indonesia mencatat bahwa sentralisasi kekuasaan pernah menimbulkan ketidakpuasan yang kemudian menjadi benih separatisme.
CSIS, dalam kajiannya, mengingatkan bahwa separatisme umumnya tumbuh pada situasi ketika daerah merasa diperlakukan hanya sebagai objek pembangunan. Sentralisasi yang berlebihan berpotensi menciptakan alienasi politik dan rasa keterasingan sosial, terutama di wilayah yang memiliki identitas kultural yang kuat. Namun, kritik tersebut perlu dibaca secara proporsional dalam konteks tantangan tata kelola negara pasca dua dekade desentralisasi.
Salah satu isu yang memantik perdebatan adalah kebijakan fiskal dan pembiayaan daerah. Laporan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang menyebut adanya penyesuaian Dana Alokasi Umum memicu diskusi mengenai apakah kebijakan tersebut akan melemahkan kemampuan daerah membiayai pelayanan publik. Demikian pula dengan pengambilalihan penanganan sengketa wilayah antarprovinsi oleh pemerintah pusat, yang dipandang sebagian kalangan sebagai pengurangan kewenangan daerah.
Di sisi lain, konsolidasi politik di tingkat pusat, mulai dari pembentukan koalisi besar hingga sinkronisasi agenda legislatif dan eksekutif membentuk situasi politik yang stabil sekaligus dominan. Bagi sebagian pihak, hal ini membawa kepastian dan efektivitas, bagi yang lain, ia mengandung potensi pembatasan ruang kritik dan kontrol.
Antara Stabilitas Nasional dan Risiko Disintegrasi
Pandangan bahwa sentralisasi akan otomatis memicu separatisme perlu diuji secara hati-hati. Desentralisasi yang luas sejak reformasi memang membuka ruang partisipasi politik daerah, namun ia juga menyisakan masalah struktural yang tidak sederhana. Dalam sektor pertambangan misalnya, pemberian kewenangan perizinan kepada kepala daerah menyebabkan pemerintah pusat menanggung sengketa hukum dengan investor asing akibat perjanjian yang cacat. Pada titik ini, sentralisasi dapat dilihat sebagai langkah korektif untuk menjaga akuntabilitas nasional di sektor-sektor strategis.
Selain itu, desentralisasi juga memproduksi fenomena yang sering disebut sebagai “raja-raja kecil”, elite lokal yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi daerah hingga menciptakan oligarki yang sulit disentuh regulasi nasional. Regulasi daerah yang bertentangan dengan kebijakan pusat menunjukkan bahwa otonomi tidak selalu identik dengan pemerintahan yang efektif dan demokratis.
Karena itu, tantangan terbesar bukan pada memilih antara sentralisasi atau desentralisasi, melainkan menemukan bentuk keseimbangan yang memperkuat daya ikat kebangsaan tanpa mematikan aspirasi lokal. Indonesia dibangun di atas kesadaran historis bahwa keberagaman adalah fondasi sekaligus tantangan. Ketika pembangunan ekonomi, distribusi sumber daya, dan representasi politik tidak merata, sentralisasi dapat memicu kecemburuan horizontal dan memunculkan kembali narasi marginalisasi daerah.
Namun, sentralisasi yang terukur dalam sektor strategis, misalnya pertahanan, sumber daya mineral strategis, dan tata kelola fiskal makro dapat menjadi instrumen untuk mencegah fragmentasi politik dan ekonomi antarwilayah. Justru yang perlu diperkuat adalah mekanisme dialog, transparansi, dan akuntabilitas yang menjamin bahwa penguatan pemerintah pusat tidak berujung pada pengabaian suara daerah.
Dalam perspektif filsafat politik, negara yang stabil bukan negara yang memusatkan kekuasaan, melainkan yang berhasil menyelaraskan pusat dan daerah dalam kerangka kepentingan bersama. Pancasila memberi pedoman yang jelas bahwa persatuan bukanlah penyeragaman, melainkan kesepakatan nilai bersama yang menghormati keragaman. Karena itu, kritik terhadap resentralisasi seharusnya tidak berhenti pada retorika ancaman separatisme, melainkan diarahkan pada bagaimana memastikan bahwa kebijakan pusat tetap membuka ruang dialog dan penghargaan atas kekhasan daerah.
Pada akhirnya, persoalan ini menuntut kedewasaan politik: pusat tidak boleh memandang daerah sebagai subjek yang harus diarahkan tanpa partisipasi, dan daerah tidak boleh terjebak dalam sentimen kedaerahan yang mengabaikan kepentingan nasional. Tantangan terbesar bukan hanya membangun struktur pemerintahan yang efektif, tetapi menjaga keutuhan imajinasi kebangsaan Indonesia. Sebab, di tengah ketimpangan ekonomi, perbedaan identitas, dan dinamika politik global yang cepat berubah, yang menentukan masa depan Indonesia bukan sekadar siapa yang memegang kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan.