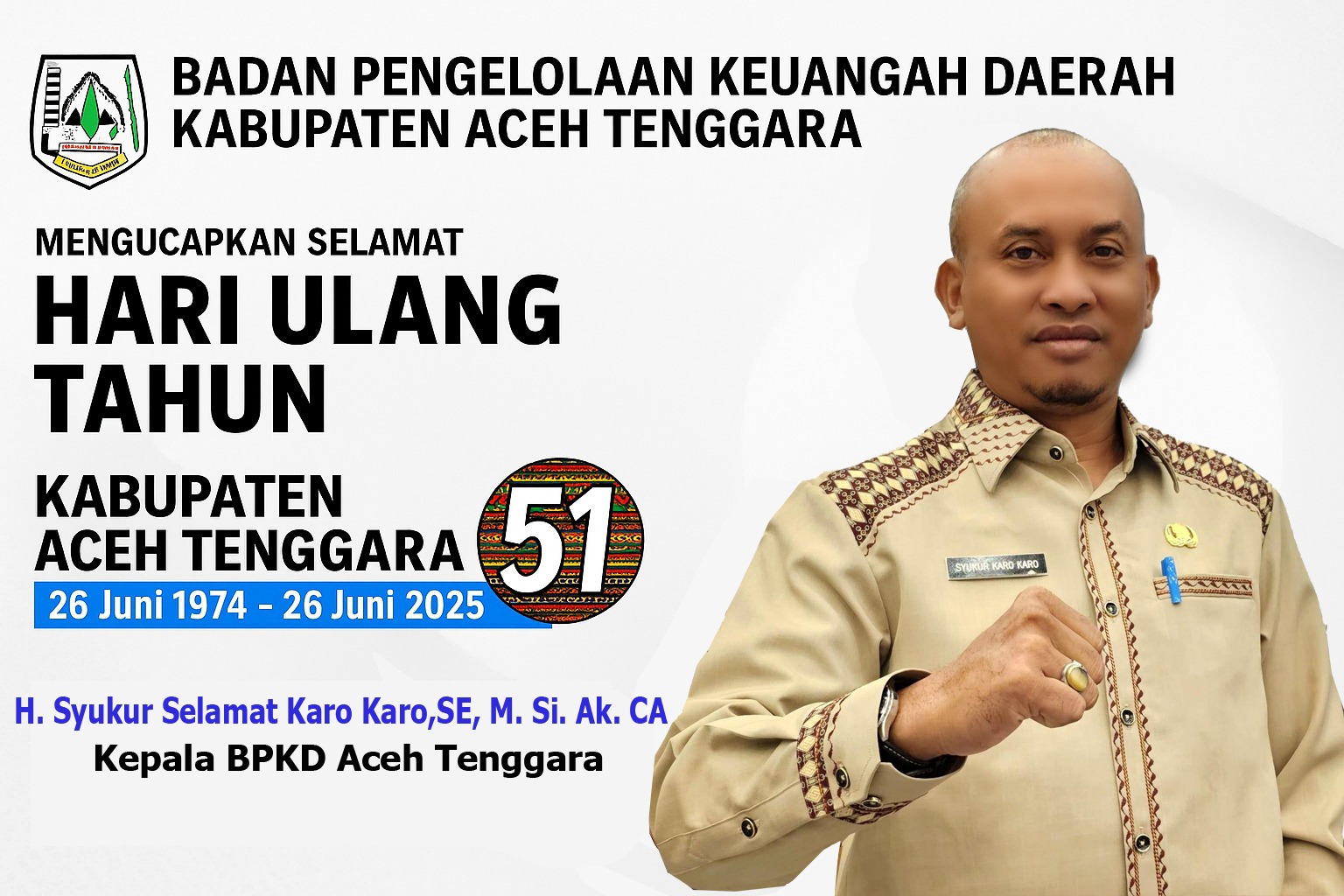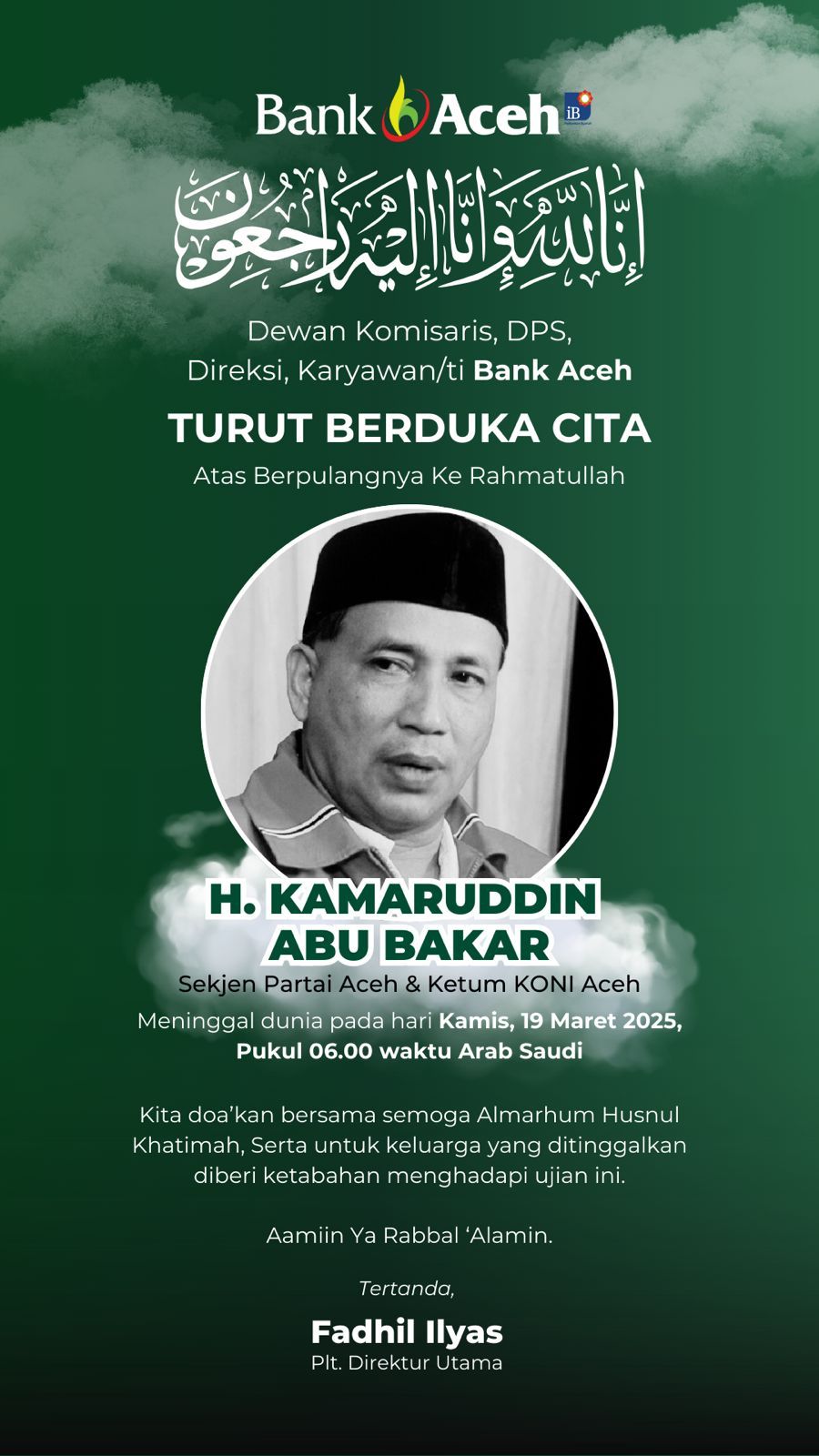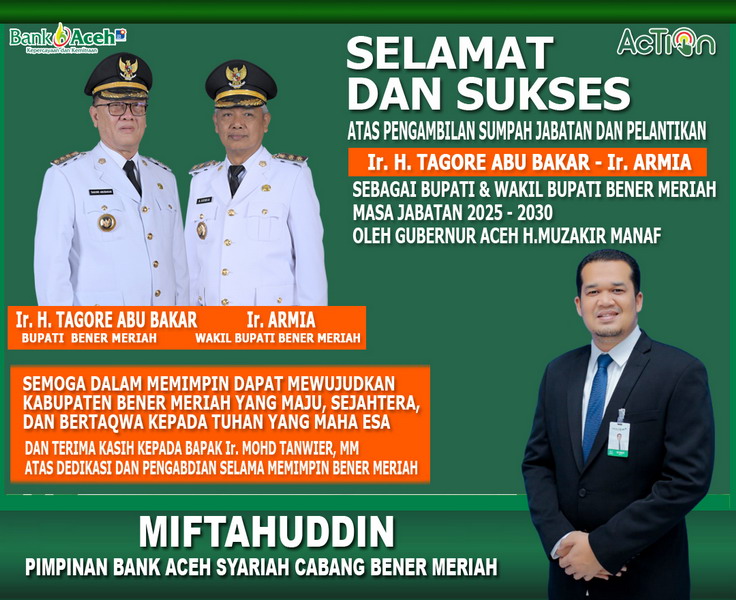Oleh: Sri Radjasa MBA (Pengamat Intelijen)
Reformasi 1998 dipuja sebagai tonggak demokrasi dan supremasi sipil. TNI, yang kala itu masih bernama ABRI, dipaksa melepaskan dwi fungsi yang selama puluhan tahun menempatkannya bukan hanya sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga mesin politik Orde Baru. Lebih dari dua dekade berlalu, pertanyaan mendasar muncul, apakah reformasi benar-benar berhasil menata ulang relasi sipil-militer, atau justru menjadikan TNI kambing hitam dari politik transisi yang belum matang?
Sejarah tidak bisa dipisahkan dari jati diri TNI. Tentara ini lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan membela kemerdekaan dari rongrongan kolonial maupun insurgensi dalam negeri. Dalam catatan sejarah militer, TNI bahkan mampu memukul mundur tiga divisi pasukan Inggris pemenang Perang Dunia II yang mencoba merebut kembali Indonesia. Namun, warisan ini kabur di tengah narasi reformasi yang menyoroti TNI semata-mata sebagai simbol represi, pelanggaran HAM, dan penghalang demokrasi. Di titik ini, reformasi lebih tampak sebagai alat dendam politik terhadap masa lalu, ketimbang instrumen rasional untuk membangun militer yang profesional dan relevan dengan tantangan zaman.
Ironisnya, slogan “TNI kembali ke barak” dipakai sebagai mantra untuk menjauhkan militer dari rakyat. Padahal, sejak lahir, TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Ketika narasi pemisahan ini terus digembar-gemborkan, muncul kecurigaan bahwa agenda tersebut bukan murni demi demokrasi, melainkan bagian dari strategi melemahkan pilar pertahanan bangsa. Bahkan, tidak sedikit analis internasional yang menilai bahwa peminggiran militer di negara-negara dunia ketiga sering kali membuka celah bagi infiltrasi kepentingan asing.
Samuel Huntington dalam The Soldier and The State membedakan antara objective control yang membuat militer kuat, profesional, namun tetap dalam kendali sipil dan subjective control yang justru melemahkan militer demi kepentingan kekuasaan sipil. Sayangnya, Indonesia lebih dekat dengan model kedua. TNI dikembalikan ke barak bukan untuk memperkuat profesionalisme, melainkan untuk menghapus pengaruh politiknya, meski dalam praktiknya elite sipil tetap memanfaatkan militer untuk kepentingan sesaat.
Isu HAM menjadi palu godam untuk mendeligitimasi TNI. Padahal sejak awal, setiap prajurit dibekali “8 Wajib TNI” yang sarat nilai kemanusiaan. Yang jarang disentuh oleh wacana publik adalah bahwa UUD 1945 tidak hanya menjamin hak individu, tetapi juga hak asasi bangsa (right of a nation) dan hak asasi negara (right of a state). Kedua hak ini hampir tak pernah diangkat dalam diskursus Barat, yang cenderung menekankan individu sambil mengabaikan hak kolektif bangsa untuk merdeka, setara, dan berdaulat. Kritik HAM pun akhirnya lebih tampak sebagai alat politik global ketimbang instrumen moral universal.
TNI juga tidak bisa sepenuhnya steril dari politik. Clausewitz dengan tegas pernah menyebut perang sebagai kelanjutan politik dengan cara lain. Artinya, militer justru harus mampu membaca dinamika politik agar dapat mengantisipasi potensi konflik. Jika TNI dipaksa benar-benar apolitis, maka TNI kehilangan kemampuan strategis untuk mengidentifikasi musuh, mendeteksi perang hibrida, dan menilai ancaman geopolitik. Dalam konteks global multipolar, ketika perang tidak lagi frontal tetapi dikemas dalam bentuk ekonomi, informasi, hingga siber, kemampuan membaca politik justru menjadi kebutuhan vital militer.
Pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar dalam merumuskan peran TNI yang sesuai dengan tuntutan zaman. Proyeksi penambahan personel TNI AD, misalnya, seharusnya diarahkan pada pembangunan satuan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yakni Komando Rayon Militer (Koramil). Koramil bukan hanya pos pertahanan, tetapi etalase TNI di tengah rakyat. Reorganisasi Koramil mendesak dilakukan, dengan memperkuat tenaga kesehatan, zeni, logistik, dan bahkan bidang olahraga. Komandan Koramil pun idealnya tidak hanya dipilih berdasarkan senioritas, tetapi juga kapasitas intelektual dan keterampilan komunikasi. Dengan begitu, TNI kembali menemukan peran sejatinya yaitu hadir bersama rakyat, menyelesaikan persoalan sehari-hari, sekaligus membina kesadaran bela negara.
Data menunjukkan belanja pertahanan Indonesia pada 2024 hanya sekitar 0,8 persen dari PDB, jauh di bawah standar NATO sebesar 2 persen, bahkan masih tertinggal dibandingkan Singapura (3,1 persen) dan Vietnam (2,3 persen). Angka ini memperlihatkan lemahnya prioritas negara terhadap pertahanan. Tanpa dukungan politik yang kuat, TNI akan kesulitan memenuhi peran strategisnya, baik dalam konteks keamanan regional maupun penguatan daya tangkal dalam negeri.
Menjelang HUT TNI ke-79, refleksi ini menjadi penting. Perayaan tidak cukup dengan parade alutsista dan seremoni. TNI harus meneguhkan kembali jati dirinya, berdiri sebagai pilar utama pertahanan negara yang dicintai rakyat dan disegani dunia internasional. Naif jika bangsa ini berharap demokrasi kokoh tanpa militer yang kuat. Reformasi seharusnya bukan amputasi sejarah, melainkan reposisi bijak: menempatkan TNI bukan sebagai ancaman demokrasi, melainkan penjaga kedaulatan. Tanpa TNI yang tangguh, demokrasi hanya akan menjadi panggung rapuh yang mudah runtuh diterpa badai global.