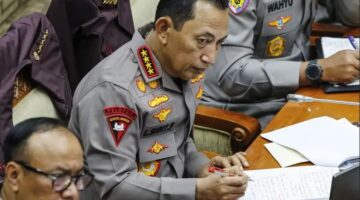JAKARTA | Kasus pengguna jasa prostitusi yang tidak membayar sesuai kesepakatan ternyata tidak dapat diproses secara pidana meskipun secara moral dipandang negatif oleh masyarakat. Dalam praktik hukum, tindakan tersebut tidak memenuhi unsur pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena tidak disertai dengan dasar hukum yang sah dalam konteks perjanjian.
Penjelasan ini disampaikan oleh konsultan hukum Siko Aryo Widianto, menanggapi pertanyaan publik yang kerap muncul terkait praktik hubungan seksual berbayar yang tidak dibarengi pembayaran sesuai nilai kesepakatan. Dalam sebuah unggahan melalui media sosialnya, ia mencontohkan kasus ketika seorang pengguna jasa seksual telah berhubungan badan secara suka sama suka tanpa unsur paksaan maupun kekerasan, tetapi hanya membayar sebagian dari nilai yang telah disepakati sebelumnya.
“Banyak yang bertanya, apakah kondisi seperti ini bisa dilaporkan dengan pasal penipuan Pasal 378 KUHP? Jawabannya tidak bisa,” ujar Siko, dalam penjelasannya yang dikutip pada Minggu (25/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan, harus ada bukti bahwa pelaku sejak awal berniat tidak membayar dan telah menyampaikan fakta atau janji palsu untuk memperoleh keuntungan. Lebih dari itu, harus ada unsur perjanjian yang sah menurut hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan tersebut, terdapat empat syarat sah perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan adanya sebab yang halal.
“Dalam konteks perbuatan prostitusi atau jasa hubungan seksual berbayar, sebabnya tidak dianggap halal secara hukum. Jadi, perjanjian jenis ini tidak memenuhi hukum sah secara perdata. Otomatis, tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut secara pidana,” jelas Siko.
Ia menambahkan, walaupun secara faktual terdapat pihak yang merasa dirugikan, hal ini masuk dalam kategori kejahatan tanpa korban langsung atau victimless crime. Hukum positif di Indonesia tidak dapat memberikan perlindungan terhadap perjanjian yang dalam dirinya mengandung perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
Dengan demikian, menurut Siko, apabila seseorang mencoba melaporkan kasus seperti ini ke kantor kepolisian, aparat tidak memiliki dasar hukum untuk menerima ataupun memproses laporan tersebut. “Kalau wanita ini atau perempuan ini melaporkan pidana ke kantor polisi karena tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan, jelas polisi tidak akan menerima laporannya, tidak akan memproses,” tegasnya.
Masalah ini mencerminkan ketegangan antara norma sosial, moral, dan batasan hukum positif yang berlaku. Di satu sisi, terdapat pengakuan akan praktik yang berlangsung secara nyata di masyarakat, namun di sisi lain, hukum tidak memberikan legitimasi terhadap aktivitas atau perjanjian yang dianggap bertentangan dengan prinsip kesusilaan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, penyelesaian perselisihan semacam ini lebih banyak bergantung pada pemahaman informal dan tidak bisa ditarik ke ranah pidana. (*)