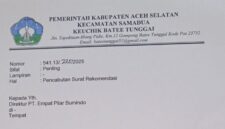Penulis : Sri Radjasa, MBA (Pemerhati Intelijen)
Seperempat abad setelah reformasi, cita-cita untuk menghadirkan Polri yang profesional, humanis, dan berjarak dari politik kekuasaan kian menjauh. Pemisahan Polri dari TNI di tahun 2000 diharapkan melahirkan aparat sipil yang melindungi rakyat, bukan menakut-nakuti mereka. Namun kini, lembaga itu justru kerap dilihat sebagai mesin kekuasaan yang menekan oposisi dan mengamankan kepentingan politik penguasa. Publik sinis menyebutnya “Parcok”, sebuah simbol bahwa penegakan hukum telah kehilangan makna moralnya.
Masalah Polri hari ini bukan sekadar deretan pelanggaran etik atau salah urus individu. Ia sudah menjadi krisis struktural dan etis. Di atas kertas, Polri memiliki sistem meritokrasi yang ideal: rekrutmen transparan, promosi berbasis kompetensi, dan pendidikan berjenjang. Namun praktik di lapangan menunjukkan sebaliknya. Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sistem ini dibengkokkan oleh politik loyalitas. Kedekatan menjadi lebih berharga daripada prestasi, dan kepatuhan pada atasan lebih penting daripada keberanian menegakkan kebenaran.
Naiknya Sigit sebagai Kapolri menandai era baru sentralisasi kekuasaan di tubuh kepolisian. Pola ini melahirkan struktur yang kaku, tertutup, dan hierarkis ekstrem. Banyak perwira berprestasi tersingkir karena tidak termasuk dalam lingkar kedekatan. Dalam situasi demikian, pendidikan kepolisian kehilangan maknanya sebagai pembentuk integritas. Ia berubah menjadi formalitas administratif untuk melegitimasi promosi yang telah ditentukan sebelumnya.
Krisis ini diperparah oleh peran politik Presiden Joko Widodo yang memanfaatkan Polri sebagai instrumen kekuasaan. Di bawah kepemimpinannya, Polri tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga mengawal stabilitas politik. Dalam Pemilu 2024, banyak pengamat mencatat tanda-tanda ketidaknetralan aparat dalam menjaga proses demokrasi. Penegakan hukum menjadi selektif, tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Maka tak heran bila kepercayaan publik terhadap Polri terus merosot.
Kritik terhadap Polri akhirnya mengarah ke dua figur utama yakni Jenderal Sigit dan Presiden Jokowi. Keduanya dianggap bertanggung jawab atas merosotnya independensi dan profesionalisme kepolisian. Kepemimpinan Sigit dinilai gagal menegakkan sistem meritokrasi dan memperkuat budaya patronase yang menggerogoti moral institusi. Sementara Jokowi dituding membiarkan Polri menjadi alat politik kekuasaan, bukan alat penegak hukum.
Kini, ketika tampuk pemerintahan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, publik menunggu langkah berani: apakah ia akan berani menata kembali Polri ke rel yang benar, atau justru membiarkannya tetap menjadi perpanjangan tangan kekuasaan lama? Reposisi menjadi kata kunci. Presiden tidak bisa sekadar melakukan reformasi kosmetik, tetapi harus menata ulang arah moral dan sistem nilai di tubuh kepolisian. Itu berarti mengganti pimpinan yang kehilangan legitimasi publik, memutus rantai loyalitas politik, dan mengembalikan Polri ke fitrah konstitusionalnya.
Langkah itu mungkin tidak populer, bahkan berisiko politik. Namun sejarah menunjukkan, bangsa tidak pernah maju tanpa keberanian moral. Reposisi Polri bukan soal balas dendam atau perebutan pengaruh, melainkan upaya menyelamatkan marwah hukum dari cengkeraman kekuasaan. Presiden Prabowo harus berani mengambil jarak moral dari warisan cawe-cawe Jokowi jika ingin menegakkan kedaulatan hukum yang sejati.
Filsuf Hannah Arendt pernah menulis, kekuasaan tanpa etika hanyalah kekerasan yang dilembagakan. Polri kini berada di tepi jurang itu, memegang kekuasaan besar, tapi kehilangan kendali moral. Padahal, legitimasi lembaga penegak hukum tidak lahir dari senjata, melainkan dari kepercayaan rakyat. Polisi bukan hanya aparat hukum, melainkan penjaga peradaban sipil.
Menata Polri berarti menata kembali moral negara. Reformasi tidak cukup jika tidak diikuti keberanian etik untuk menolak intervensi politik. Bangsa ini butuh polisi yang berani menegakkan hukum, bukan menegakkan perintah. Polisi yang berdiri di sisi rakyat, bukan di belakang penguasa.
Dan ketika publik bertanya, “Siapa yang salah ketika Polri jadi parcok?”, jawabannya tak lagi sederhana. Yang salah bukan hanya orangnya, tapi juga keberanian kita sebagai bangsa untuk berkata cukup, yaitu cukup bagi politik yang mencengkeram hukum, cukup bagi kekuasaan yang menodai seragam pengayom rakyat. Sebab hanya dengan keberanian moral itulah Polri bisa kembali menjadi milik rakyat, bukan milik kekuasaan.