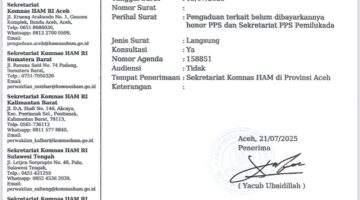JAKARTA — Denting palu hakim belum kering, tapi suara protes sudah menggema dari Gedung Merah Putih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak diam atas vonis terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Bukan karena ringannya hukuman, tapi karena sebagian dakwaan mereka mental di tangan majelis hakim.
Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat sore (25/7), hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun enam bulan penjara kepada Hasto. Ia dinyatakan terbukti terlibat dalam pusaran suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku melalui jalur pergantian antarwaktu. Namun, dakwaan perintangan penyidikan—pasal krusial yang disiapkan KPK untuk menunjukkan keseriusan upaya menghalangi penegakan hukum—justru ditolak hakim.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan keberatan resmi pada malam hari, hanya beberapa jam setelah palu diketuk. Ia menyebut unsur pidana dalam dakwaan tersebut seharusnya terpenuhi. “Persangkaannya jelas, bunyi pasalnya juga jelas: ‘barang siapa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan, langsung atau tidak langsung’,” katanya di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan.
Dalam konstruksi perkara KPK, Hasto bukan hanya tokoh politik yang berada di belakang pengaturan PAW Harun Masiku. Ia juga dianggap sebagai aktor yang secara sadar dan sistematis menghalangi kerja penyidik. Salah satu buktinya adalah dugaan upaya menyembunyikan alat komunikasi dan pengaburan informasi kepada tim penyelidik.
Tapi majelis hakim punya tafsir berbeda. Mereka menilai perbuatan Hasto—sekalipun terindikasi mengarah pada penghalangan penyidikan—terjadi saat perkara masih berada di tahap penyelidikan. Artinya, menurut hakim, belum masuk ke dalam domain pasal perintangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Bagi KPK, argumentasi itu hanya soal waktu administratif. Setyo menegaskan bahwa tindakan nyata mencegah dan merintangi sudah terjadi. “Kami yakin ada upaya nyata. Jadi, kurang bukti apa lagi?” ujarnya, tak bisa menyembunyikan kekecewaan.
Mereka mengaku akan mempelajari salinan putusan secara lengkap sebelum menentukan langkah selanjutnya. Namun, di balik sikap diplomatis itu, ada kekhawatiran bahwa keputusan ini akan menjadi preseden buruk. Sebab, jika fase penyelidikan tidak dilindungi secara hukum dari upaya penghalangan, maka kerja KPK bisa lumpuh sejak langkah pertama.
Hasto sendiri, seperti dalam setiap sidang sebelumnya, menampakkan wajah tenang. Tim kuasa hukumnya menyebut putusan itu sebagai bukti lemahnya pembuktian jaksa atas dakwaan tambahan. Bahkan, mereka menuding KPK menyusun narasi berdasarkan asumsi politik, bukan fakta hukum.
Kubu pembela menyoroti cara jaksa membangun argumen dengan mendatangkan penyelidik dan penyidik sebagai saksi, yang menurut mereka melanggar prinsip netralitas dan keadilan. “Bahkan saksi-saksi kami diabaikan oleh hakim. Ini kriminalisasi,” ujar salah satu anggota tim pembela.
Di sisi luar ruang sidang, beberapa kelompok massa pendukung Hasto menggelar aksi spontan. Mereka membawa keranda, spanduk bertuliskan “Hasto Bukan Penjahat” dan orasi yang menuduh proses hukum sebagai alat kekuasaan menjelang pemilu. Namun narasi perlawanan itu tak mampu membungkam pertanyaan publik yang lebih besar: di mana Harun Masiku?
Sudah lima tahun Harun hilang. KPK dan kepolisian seperti menari di tempat. DPO yang dikeluarkan sejak 2020 hanya menjadi dokumen formal yang tak lagi menimbulkan efek kejut. Bahkan, upaya KPK dalam perkara Hasto dianggap sebagai jalan memutar untuk menghidupkan kembali isu Harun yang nyaris dilupakan.
Vonis ini, pada akhirnya, menjadi babak terbaru dalam drama panjang hubungan kuasa, politik, dan hukum. Satu pihak dinyatakan bersalah, satu pasal gagal ditegakkan, dan satu tokoh kunci tetap hilang entah ke mana.
Dalam dunia peradilan yang semakin kabur batas antara manuver dan keadilan, putusan ini menandai tarik-ulur baru antara lembaga penegak hukum. Dan publik, seperti biasa, hanya bisa menonton sambil bertanya: siapa sebenarnya yang sedang diadili? (*)